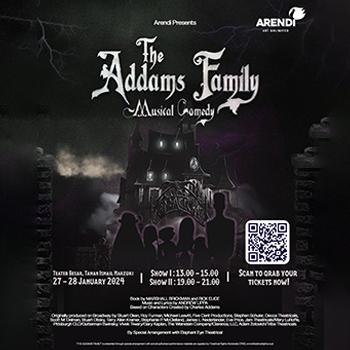Pramoedya Ananta Toer, Menulis untuk Keabadian
“Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” Itulah salah satu quote terpopuler sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Meski telah berpulang 11 tahun lalu, sosoknya sulit dipisahkan dari dunia sastra Indonesia. Tulisan Pram dikenal tajam dan berani mengkritik pemerintah, meski itu bikin dia sering keluar-masuk penjara.
Lebih 50 judul buku karya Pram pun sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa. Termasuk tetralogi “Bumi Manusia”, “Anak Semua Bangsa”, “Jejak Langkah”, dan “Rumah Kaca”, yang ia tulis selama masa pembuangan di Pulau Buru. Buku-buku itu sempat dilarang beredar di Indonesia.
Pram lahir di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Nama aslinya Pramoedya Ananta Mastoer. Cita-citanya hanya ingin menjadi petani. Ayah Pram, Mastoer, adalah seorang guru yang juga merupakan tokoh Institut Boedi Oetomo. Meski anak Pak Guru, Pram bukan murid yang pandai. Dia bahkan sempat tiga kali nggak naik kelas. Pendidikan SD di Taman Siswa yang harusnya hanya tujuh tahun, dia selesaikan dalam waktu 10 tahun. Merasa putra sulungnya terlalu bodoh untuk bersekolah, Mastoer menolak mendaftarkan Pram ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), sebutan untuk SMP pada masa kolonial Belanda.
Mengandalkan sedikit tabungan dari uang pemberian ibunya sebagai penjual nasi, Pram bisa melanjutkan pendidikan. Memang bukan ke MULO, melainkan ke sebuah sekolah telegraf Radio Vakschool (Sekolah Kejuruan Radio) di Surabaya. Pram lulus dalam waktu 1,5 tahun saja. Dia menjalani dinas wajib di seksi radiotelegraf dari Stadswacht (Pertahanan Sipil Kota) di kampung halamannya. Setelah ibunya meninggal, Pram pindah ke Jakarta. Dia diterima bekerja sebagai juru ketik di Kantor Berita Domei milih Jepang.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, Pram bergabung dalam kelompok militer di Jawa. Dia mulai aktif menulis cerpen dan buku sepanjang karier militernya. Pada 1947, Pram pertama kali dijebloskan ke penjara. Ia meringkuk di Penjara Bukitduri di tepi sungai Ciliwung di Jatinegara selama setahun. Tapi semangat Pram untuk menulis nggak pernah luntur.
Di balik jeruji besi, Pram tetap rajin menulis. Dia menyerahkan karya-karyanya pada rekan yang membezuk ke tahanan untuk diamankan. Bebas dari penjara, Pram menikah. Dia lalu tinggal di Belanda mengikuti program pertukaran budaya. Saat kembali ke Indonesia, gaya penulisannya berubah. Pram juga bergabung dengan Lekra, sebuah organisasi sayap kiri Indonesia.
Sejak itulah Pram terus keluar-masuk penjara gara-gara tulisan maupun urusan politik. Meski belasan tahun ditahan, Pram tidak pernah berhenti menulis. Berbagai karya ia lahirkan dari balik jeruji. Buku-buku itu kerap dicekal pemerintah. Saat bebas dari penjara pada 1979, Pram tetap dikenai status tahanan rumah di Jakarta sampai 1992, berlanjut menjadi tahanan kota dan tahanan negara hingga 1999.
Sepanjang kariernya sebagai penulis, Pram mendapat banyak penghargaan internasional. Bahkan, nyaris pula meraih Nobel Sastra pada 2004 dan 2005. Hampir seluruh novel dan cerpen Pram terinspirasi dari pengalaman hidupnya sehari-hari. Beberapa tulisan bahkan bersifat semi-otobiografi. Mulai tentang sejarah Indonesia, konflik korupsi, sampai penyiksaan terhadap kaum minoritas Tionghoa. Itulah yang membuat dia sering menuai kontroversi.
Hingga usia lanjut, Pram masih saja aktif menulis. Karya-karya terakhirnya antara lain “Panggil Aku Kartini Saja” (2003), “Jang Sudah Hilang” (2004), dan “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels” (2006). Pram meninggal dalam usia 81 tahun di Jakarta, 30 April 2006. Dari sembilan anak hasil pernikahan dengan Maemunah Thamrin, keponakan pahlawan nasional MH Thamrin, belum satu pun yang mewarisi jejak Pram sebagai penulis.
HAFIDA INDRAWATI
ILUSTRASI: SUPERKIDS INDONESIA


 English
English